Beberapa hari terakhir, linimasa kita gaduh. Kata “ro’an” tiba-tiba jadi momok. Media, akun-akun aktivis, dan para komentator dadakan berbondong-bondong menyebutnya “eksploitasi.” Padahal mereka tak tahu, ro’an bukan pekerjaan paksa tapi bagian dari ruh pesantren itu sendiri. Semua bermula dari tragedi di Pondok Al-Khoziny. Satu insiden yang seharusnya disikapi dengan empati, justru digoreng dengan bumbu tuduhan. Muncul narasi: “Santri dipaksa kerja bangunan, tanpa upah, tanpa alat keamanan.” Lalu dengan cepat, semua pesantren ikut ditarik dalam pusaran tuduhan yang sama: memperbudak santri atas nama pengabdian.
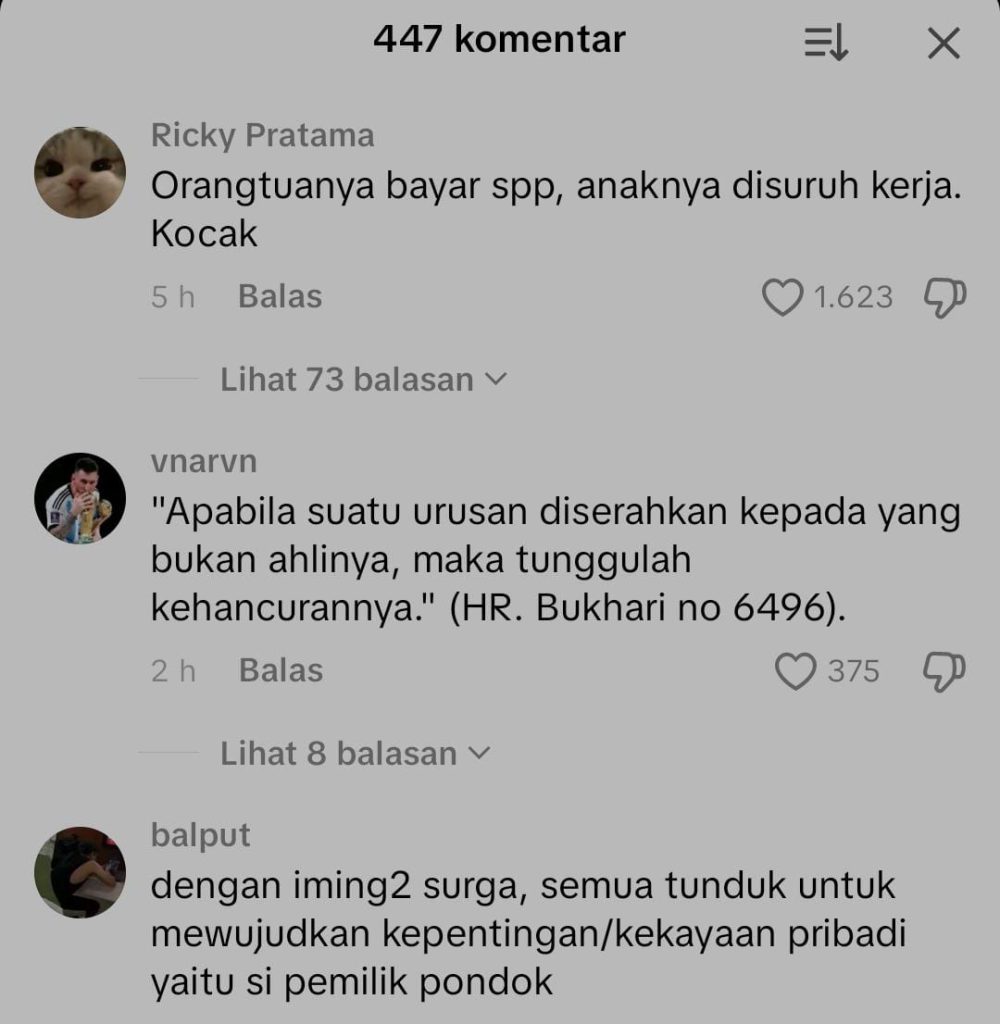
Padahal, siapa pun yang pernah mondok tahu ro’an itu bukan beban. Itu tradisi. Itu bagian dari pendidikan karakter yang tak tertulis di kurikulum, tapi tercetak di hati. Ro’an di pesantren bukanlah santri dijadikan kuli bangunan. Santri yang ikut ro’an umumnya hanya laden istilah di dunia pertukangan untuk pembantu kerja, bukan tukang utama.
Mereka sekadar ngaduk semen, ngangkat batu, potong kayu, atau bantu ngecor. Sementara hal-hal teknis seperti pengukuran, dimensi, dan struktur tetap ditangani oleh tukang profesional yang dibayar secara resmi.
Kalau pun santri terlibat, itu karena rela. Karena cinta pada pondoknya. Karena di situ mereka merasa ikut membangun rumahnya sendiri. Ada kepuasan batin ketika tangan yang biasa memegang kitab, hari itu menggenggam cangkul untuk pondok yang selama ini membesarkannya. Orang luar melihat peluh dan debu di wajah santri sebagai penderitaan. Santri sendiri melihatnya sebagai kehormatan.
Lucunya, dunia memuji Jepang karena anak-anak sekolahnya membersihkan kelas sendiri. Mereka menyapu, mengepel, mengelap kaca, bahkan membersihkan toilet. Tak ada petugas kebersihan di sekolah-sekolah Jepang.
Dan dunia barat bertepuk tangan: “Lihat, Jepang mendidik tanggung jawab dan disiplin sejak dini.” Tapi ketika santri mencangkul halaman, menyapu asrama, atau membantu pembangunan pesantren media malah menyebutnya perbudakan.
Padahal esensinya sama: pendidikan karakter. Bedanya, pesantren tak punya juru bicara yang lihai di depan kamera.
Tak punya humas dengan pencahayaan sinematik untuk menjelaskan bahwa ro’an itu bukan kerja paksa, tapi kerja ikhlas. Santri-santri di pelosok itu tidak sedang dieksploitasi. Mereka sedang belajar makna gotong royong yang sudah hilang di kota.
Ro’an bukan sekadar tenaga. Ia adalah latihan hidup. Di situ santri belajar disiplin, kebersamaan, tanggung jawab, dan kesadaran sosial. Santri yang dulu canggung memegang sekop, lama-lama jadi terampil. Yang awalnya sekadar “laden,” kelak bisa membangun masjidnya sendiri di kampung. Bukankah itu sama saja dengan “praktik kerja lapangan,” versi pesantren? Bahkan lebih bermakna karena dibungkus keikhlasan. Tidak ada surat tugas, tidak ada raport, tidak ada sertifikat. Yang ada hanya kalimat lirih dari kiai: “Niatmu lillah, ya nak.”
Tidak semua santri datang ke pondok dengan bekal materi. Sebagian datang dengan doa dan pasrah bongko’an seadanya. Mereka tidak mampu membayar penuh, tapi mampu berterima kasih dengan tangan dan tenaga. Dan pondok tidak pernah menuntut. Yang ingin membantu, silakan. Yang ingin fokus ngaji, juga dipersilakan. Itulah wajah asli pesantren, sederhana tapi tulus. Dan di situlah nilai yang tidak dimengerti oleh mereka yang melihat dari balik layar kaca bukan dari realita.
Jadi mari kita luruskan, Ro’an bukan perbudakan. Ia bagian dari tarbiyah pendidikan jiwa dan adab. Kalau semua kerja diukur dengan upah, maka kasih sayang orang tua pun seharusnya digaji. Kalau semua keringat dianggap eksploitasi, maka gotong royong takkan pernah punya tempat. Rasulullah ﷺ bersabda:
“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain.” (HR. Ahmad)
Dan manfaat itu, sering kali lahir dari tangan-tangan yang kotor karena tanah, tapi bersih karena niat. Ro’an adalah cermin, Bahwa kemerdekaan santri bukan diukur dari seberapa banyak ia tahu, tapi seberapa dalam ia peduli.
Bahwa membangun pesantren bukan kerja paksa, tapi kerja cinta. Karena kalau yang disebut “eksploitasi” adalah keringat santri yang menetes untuk pondoknya sendiri, maka sesungguhnya yang paling miskin bukan santri tapi kita, yang sudah kehilangan makna gotong royong itu sendiri.
kabar Terkini dari Ma’had Aly Andalusia Leler Banyumas
Ikuti perkembangan terbaru seputar akademik, kegiatan santri, dan dinamika organisasi di Ma’had Aly Andalusia melalui website resmi: maalyandalusia.ac.id. dan malyjurnalistik.com
Temukan informasi aktual, artikel inspiratif, dan liputan kegiatan langsung dari sumbernya. Jangan lupa ikuti juga media sosial kami untuk update cepat dan konten menarik setiap harinya.
Follow Media Sosial









Tinggalkan Balasan